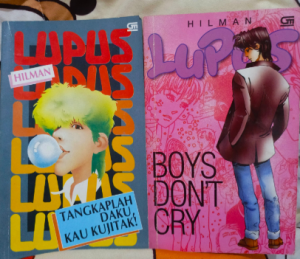Foto: Canva
Kita semua tahu, duduk di bangku kuliah itu tidak otomatis membuat seseorang dewasa secara emosional atau cerdas secara intelektual. Hampir semua orang paham bahwa empat tahun perkuliahan hanyalah periode singkat—tidak sepenting itu, tetapi sayang jika dilewatkan hanya untuk bermalas-malasan.
Kali ini, penulis yang masih “bau ijazah” alias fresh graduate ingin mengajak pembaca sedikit terusik, gelisah, bahkan mungkin merasa tidak nyaman. Sebelum lanjut membaca, silakan teguk segelas air—biar kepala tetap dingin meski hati bisa saja panas. Anggaplah ini ruang saya untuk menyampaikan opini. Dan tentu, bila pembaca punya opini tandingan, saya akan senang membacanya. Diskusi itu menyenangkan, bukan? Jadi, mari bersulang!
Mari mulai dari perpeloncoan. Ya, saya akan membuka dengan kasus yang paling fresh from the oven dari kampus saya, Universitas Sriwijaya (Unsri). Baru-baru ini, beredar video yang menampilkan adegan “ciuman massal”. Ya, kalian tidak salah baca. Saat tulisan ini dirilis, seharusnya video tersebut sudah tersebar ke mana-mana, dan tentu tidak sulit untuk ditemukan.
Lucunya, saya mengira perpeloncoan itu biasanya berupa push-up di lapangan, disiram air jamu basi, atau orasi berapi-api yang membuat tenggorokan serak. Tapi, rupanya zaman sudah berubah, kreativitas senior kampus berhasil melahirkan tradisi baru yang entah hasil bertapa yang melahirkan antara “ekstrakurikuler cinta” atau “praktikum biologi”. Rasanya seperti menonton eksperimen sosial di YouTube, bedanya ini nyata dan tidak dibuat buat.
Biar saya katakan dengan jelas, kalau kamu lebih tua satu tahun—atau bahkan sepuluh tahun sekalipun, itu tidak serta-merta menempatkanmu di atas orang yang lebih muda. Merasa lebih hebat hanya karena faktor umur adalah salah satu sifat cringe yang seharusnya dihindari oleh siapa pun yang mengaku sudah matang secara emosional dan mampu berpikir logis.
Rolf Dobelli, dalam bukunya The Art of Thinking Clearly, menulis bahwa berpikir logis itu soal menghindari jebakan bias dan ilusi kognitif yang membuat kita merasa lebih pintar daripada kenyataannya. Nah, kalau cuma bermodal angka umur lalu merasa sah jadi “penguasa junior”, itu jelas bukan logika, melainkan ilusi keagungan yang setara dengan percaya horoskop bisa menentukan nasib karier. Logika yang sehat mestinya dipakai untuk menimbang argumen, bukan untuk menghitung berapa lama kamu sudah mondar-mandir di kampus.
Tapi, mahasiswa kita memang tidak pernah benar-benar diajarkan berpikir logis sejak duduk di bangku SD. Jadi wajar saja kalau kemampuan itu terasa berat—ibarat mobil tua bangka (motuba) yang tiba-tiba diseret ikut balapan Formula 1. Bunyi mesinnya saja sudah kasihan, apalagi disuruh ngebut.
Saya akan tutup bagian ini dengan dua poin. Pertama, saran kegiatan yang memang ”mahasiswa banget” tetapi tidak perlu menguras kapasitas otak secara berlebihan—setidaknya jauh lebih masuk akal daripada ritual absurd seperti “ciuman massal”. Kedua, cara memandang sekaligus melewati budaya aneh nan konyol ini bagi para mahasiswa baru (maba), supaya tidak ikut terjebak dalam lingkaran setan senioritas yang lebih mirip drama sinetron daripada dunia akademik.
Pertama, sarannya sederhana saja, main tamiya, adu beyblade, atau merakit model kit. Percayalah, kegiatan itu jauh lebih sehat ketimbang dipaksa berciuman massal di bawah sorakan senior. Selain bisa melepas stres, bonusnya juga ada—tangan lebih terampil, imajinasi terasah, dan yang paling penting: harga diri tetap utuh.
Kedua, untuk para maba, ketahuilah bahwa kakak tingkat (kating) sebenarnya tidak memberi kontribusi apa pun dalam perkuliahanmu. Bisa saja besok kalian malah duduk bersebelahan di kelas yang sama, jadi apa gunanya merasa inferior? Mulailah belajar menetapkan ideologi dan prinsip sejak dini. Seperti kata Derek Sivers: “F*** yeah or hell no.” Jangan jadi orang yang mudah terjebak rasa “ga enakan”, apalagi sampai merugikan dirimu sendiri.
Lagipula, melawan kating yang bersikap semena-mena itu tidak salah. Justru membiarkan kesalahan hanya membuatmu sama salahnya dengan pelaku. Toh, kalian sudah cukup dewasa untuk tahu mana yang waras dan mana yang tidak. Kalau memang belum terbiasa berpikir kritis, mulailah dari satu langkah sederhana: menolak ide tidak masuk akal dari kating yang menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power).
Nah, bicara soal abuse of power, ada satu ranah lain yang tidak kalah seru: organisasi mahasiswa. Masih berhubungan dengan poin di atas, tetapi kali ini kita bedah lebih detail bagaimana organisasi kampus sering tampil manis dengan jargon “kekeluargaan”, padahal kadang lebih panas dari drama reality show. Jadi, tolonglah wahai ketua organisasi, kalian sebenarnya ingin berkembang… atau sekadar berkembang biak?
Dan sebelum ada yang nyeletuk, pertanyaan ini tidak datang dari mahasiswa kupu-kupu atau quiet quitter organisasi. Saya kebetulan dua tahun memegang posisi strategis di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat universitas, jadi cukup tahu bagaimana “dapur” organisasi itu berasap—kadang dengan aroma perjuangan, kadang lebih mirip asap knalpot yang membuat sesak napas.
Meskipun demikian, saya tetap percaya bahwa organisasi adalah tempat individu berkembang, lalu bersama-sama maju untuk menghasilkan impact yang lebih besar secara kolektif. Tidak perlu menjadi keluarga, tidak perlu menganggap saya kakak, ayah, atau peran keluarga lainnya. Saya tidak memberi makan anggota saya, maka jelas kita bukan keluarga.
Organisasi seharusnya berjalan dengan logika kerja sama, bukan drama sinetron keluarga. Kita diikat oleh visi, misi, dan tujuan bersama, bukan oleh panggilan “abang” atau “bapak” yang ujung-ujungnya hanya menjadi tameng untuk menuntut penghormatan tanpa alasan. Kalau memang ingin dihormati, buktikan lewat kerja dan gagasan, bukan lewat kartu nama jabatan.
Soal relasi? Rasanya tidak perlu terlalu di glorifikasi, apalagi kalau hanya di tingkat fakultas atau jurusan. Toh kalian bisa bertemu setiap hari—mau di kelas, kantin, atau parkiran. Memang, tidak menutup kemungkinan mereka akan membantu kamu di masa depan, tapi relasi yang cuma muter di satu kolam itu sebenarnya bukan relasi yang membuka peluang baru, melainkan sekedar “kenal lingkungan”. Relasi sejati mestinya lintas batas, membuka jendela baru, bukan sekadar main air di ember yang sama. Kalau masih berkutat di lingkaran kecil lalu menyebutnya networking, itu ibarat ganti-ganti filter Instagram tapi tetap selfie di kamar yang sama—gaya boleh beda, tapi pemandangannya itu-itu saja.
Maba tentu akan merasa hebat jika bisa masuk banyak organisasi. Hari ini ikut yang A, besok daftar yang B, lalu bangga bisa gonta-ganti PDH tiap hari seolah-olah sedang jadi model katalog seragam. Tapi sayangnya, sering kali itu semua tanpa esensi. Ujung-ujungnya jadi quit quitters—mundur pelan-pelan setelah sadar bahwa organisasinya lebih banyak drama tidak penting ketimbang progres nyata, apalagi kalau sudah sampai tahap disuruh melakukan ciuman massal, jelas makin absurd. Hehe.
Jadi, untuk para maba: santai saja, tidak perlu ambil pusing soal organisasi dalam kampus atau organisasi aneh-aneh yang sibuk jual jargon ketimbang kerja nyata. Temukan ruang yang benar-benar membuatmu berkembang, bukan tempat yang sibuk mengklaim diri sebagai “keluarga”. Ingat, kamu kuliah untuk memperbaiki pola pikir, melatih nalar, dan menyiapkan masa depan. Kalau tujuannya cuma cari keluarga, ya nikah saja, tidak perlu repot-repot kuliah.
Kalau tadi kita bahas perpeloncoan dan organisasi, sekarang mari geser ke ruang kelas. Ironisnya, di ranah akademik pun sering kali tidak kalah absurd. Bayangkan: kuliah yang isinya cuma mendengar teman presentasi, padahal presentasinya hasil copy-paste dari AI. Materinya tidak dipelajari, slide sekadar formalitas, bahkan daftar pertanyaan diskusi pun sudah disiapkan oleh AI. Pada titik ini, dosen dan mahasiswa seolah sedang main drama: pura-pura serius, padahal sama-sama tahu skripnya ditulis oleh mesin.
Lalu, bagaimana mahasiswa bisa berdiskusi secara sehat kalau pertanyaan saja dibuat, dijawab, dan disetting oleh AI? Akhirnya, kelas jadi lebih mirip roleplay ketimbang ruang belajar. Parahnya, ketika ada yang benar-benar mengajukan pertanyaan serius, ia malah dicap “sok pintar” oleh teman sekelas. Inilah budaya crab mentality ala perkuliahan: kalau ada yang mencoba naik sedikit, langsung ditarik ramai-ramai ke bawah supaya semua tetap sama-sama tenggelam di kubangan mediokritas.
Maka dari itu, untuk para maba, jangan terlalu berharap kelas menjadi ruang belajar ideal karena sebagian besar sudah berubah menjadi panggung roleplay dengan naskah dari ChatGPT atau AI lainnya. Kalau memang ingin belajar sungguh-sungguh, carilah ruang diskusi yang organik: tanyakan langsung ke dosen di luar jam kuliah, ikut diskusi rutin di komunitas, atau bergabung ke forum yang membuat kepala panas karena argumen, bukan karena proyektor rusak.
Percayalah, belajar lebih nyata ketika kamu keluar kelas: di kantin sambil debat receh yang tiba-tiba jadi serius, di komunitas baca yang tidak peduli akan jabatanmu, atau bahkan di grup nongkrong yang obrolannya bisa lebih kritis daripada satu semester mata kuliah wajib. Karena di kelas, kadang yang betul-betul belajar justru AI-nya—mahasiswanya cuma numpang absen.
Pada akhirnya, kampus bukanlah tempat sakral yang otomatis membuat orang dewasa atau cerdas. Ia hanya panggung besar dengan tiga babak utama: perpeloncoan yang dibungkus jargon “tradisi”, organisasi yang sibuk jualan “kekeluargaan”, dan ruang kelas yang makin mirip roleplay dengan naskah dari AI. Semua terlihat serius, tapi sering kali absurd—dan kalau kita jujur, kadang lebih lucu daripada sinetron prime time.
Untuk para kating yang doyan merasa berkuasa, mari tenang: umurmu hanya angka, jabatanmu hanya sementara, dan gagasan yang keliru tetap keliru meski diteriakkan lewat pengeras suara. Hormat itu datang dari integritas, bukan dari paksaan.
Dan untuk para maba, sadarilah sejak awal: kampus bukan keluarga, kating bukan nabi, organisasi bukan rumah, dan kelas bukan satu-satunya tempat belajar. Tugasmu bukan ikut-ikutan arus absurditas berjamaah, akan tetapi menemukan ruang di mana kamu benar-benar tumbuh, entah lewat komunitas, diskusi kecil, atau sekadar berani berkata “tidak” pada budaya yang jelas-jelas tidak masuk akal. Karena kalau tidak, kamu hanya akan menjadi penonton setia di drama kampus, ikut tertawa saat panggungnya kocak, tapi lupa bahwa masa depanmu tidak ditulis oleh senior, organisasi, atau AI—melainkan oleh dirimu sendiri.
Penulis: Hanif Nurrahman
Editor: Nabila Dwi Lestari